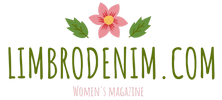Kazus Zurabishvili: Mengapa presiden tidak cukup untuk menjadi seorang wanita?

Dmitry Kurkin
"Untuk pertama kalinya seorang wanita terpilih menjadi presiden Georgia" - tidak perlu menjadi visioner untuk memprediksi bahwa berita utama tentang kemenangan Salome Zourabichvili akan menjadi seperti itu. Isu jender mau tidak mau muncul ke permukaan, meskipun ini jauh dari satu-satunya sudut di mana pemilihan ras dapat dilihat (pemimpin oposisi Grigol Vashadze memimpin untuk waktu yang lama, dan sekarang para pendukungnya membantah hasilnya, menuduh lawan memberikan tekanan pada pemilih dan menggunakan sumber daya administratif) atau angka presiden yang baru terpilih - kandidat dari partai yang berkuasa; seorang wanita Prancis asli dengan akar Georgia, yang untuk waktu yang lama diperlakukan dengan prasangka di tanah air bersejarah mereka; sebuah kebijakan yang oleh beberapa ahli dianggap sebagai anak didik pro-Kremlin, terlepas dari pernyataannya tentang pemulihan hubungan dengan Eropa. Tapi dekomposisi ini nanti, dalam paragraf yang jauh - dan "presiden wanita" akan pergi dulu. Meskipun, secara historis, wanita dalam kebijakan Georgia, dari Ratu Tamara hingga Nino Burjanadze, telah memainkan peran penting.
Penekanan pada gender umumnya dapat dimengerti. Ketidakseimbangan gender dalam politik masih terlalu besar untuk diabaikan: menurut PBB, pada Juni 2016, pangsa perempuan di kalangan anggota parlemen di seluruh dunia hanya 22,8 persen - dua kali lipat dua puluh tahun yang lalu, tetapi masih sangat jauh dari paritas apa pun. Sementara itu, kesetaraan gender dalam masyarakat terutama masalah kekuasaan, termasuk politik. Dan oleh karena itu, dari setiap pemimpin nasional terpilih, perempuan diharapkan secara default untuk pernyataan tentang "agenda perempuan". "Presiden perempuan pertama dalam sejarah negara" bukanlah garis dalam biografi yang diproyeksikan sebagai tanggung jawab: jika seorang wanita tidak memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kekuasaan, lalu siapa lagi?
"Faktor wanita" masih sangat mempengaruhi hasil pemilu - jika Hillary Clinton adalah seorang pria, kampanyenya di negara-negara konservatif bisa jauh lebih sukses. Namun, selama setengah abad terakhir, perempuan dalam politik tinggi, jika mereka belum mencapai kesetaraan, sudah pasti tidak eksotis lagi. Sejak masa Sirimavo Bandaranaike - wanita pertama yang menjadi kepala negaranya (Sri Lanka) sebagai hasil pemilihan umum, dan bukan warisan kekuasaan - wanita telah menjadi perdana menteri dan presiden di lebih dari tujuh puluh negara di dunia. Dan jika sebelum Indira Gandhi dan Margaret Thatcher sendiri merupakan pengecualian yang langka, dan biografi mereka adalah dasar yang sudah jadi untuk cerita-cerita yang menginspirasi, maka pada tahun 2018 tiba saatnya untuk menyerah dengan kejutan dan kekaguman yang dipalsukan terhadap "wanita dalam politik".
Dan bukan hanya ada cukup konservatif di antara wanita yang merupakan pemimpin dunia yang mengadopsi aturan permainan dan retorika dari kolega pria mereka ("Emansipasi wanita adalah omong kosong besar. Pria melakukan diskriminasi. Mereka tidak bisa melahirkan anak, dan sulit seseorang akan dapat melakukan sesuatu dengan ini ", - kata-kata, dalam kepengarangan yang Anda dapat curigai troll Facebook, sebenarnya milik Golda Meir, Perdana Menteri Israel keempat), meskipun mereka juga menetapkan iklim tidak sehat yang mendukung misoginiy internal karena itu perempuan tidak hanya memenangkan pemilihan - mereka bahkan takut untuk berpartisipasi di dalamnya.
Proporsi perempuan dalam kekuasaan tidak berkorelasi kuat dengan kekuatan nyata perempuan atau peningkatan hak-hak mereka.
Preseden untuk pemilihan seorang wanita sebagai kepala negara adalah penting - dan karena masing-masing contoh ini menambah celah pada “panci kaca”, dan karena semakin sering wanita muncul di puncak, semakin normal situasinya ketika seorang wanita berada di pucuk pimpinan negara (atau dalam kasus Perdana Menteri Selandia Baru, Jasinda Ardern, ibu yang bekerja). Sebaliknya, ketika tidak ada seorang pun di negara ini yang secara serius mempertimbangkan untuk memilih seorang wanita sebagai presiden (seperti di Rusia saat ini), ini berbicara tentang ketidaksetaraan jender lebih dari angka-angka keterwakilan.
Jika kita berbicara tentang angka - perhitungan statistik tidak boleh menyesatkan. Proporsi perempuan dalam kekuasaan tidak begitu kuat berkorelasi dengan kekuatan nyata perempuan atau peningkatan hak-hak mereka. Catatan perwakilan perempuan di parlemen (lebih dari dua pertiga kursi) baru-baru ini dipegang oleh Rwanda, sebuah negara yang tetap menjadi salah satu yang terburuk di dunia dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Penekanan pada jenis kelamin presiden atau perdana menteri (halo untuk materi baru-baru ini tentang Presiden Kroasia Kolind Grabar-Kitarovic) mengatakan bahwa bias politik seksis masih dianggap sebagai norma dan tidak akan usang dalam waktu dekat. Menjadi politisi wanita di abad ke-21 tidak cukup lagi. Pada tingkat politik nasional, seseorang dengan wewenang layak meminta - terlepas dari jenis kelamin (atau, dalam hal ini, seksualitas dan etnisitas: Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar, seorang gay yang secara terbuka berakar di India, menjadi contoh yang sangat baik tentang bagaimana minoritas dapat dikombinasikan dengan pandangan politik yang cukup konservatif). Dalam banyak kasus, ini kurang penting daripada nuansa lain dari latar belakang politik, pendaftaran partai dan pernyataan publik tentang masalah-masalah utama. Bagaimanapun, ada cukup banyak politisi perempuan di Rusia, tetapi Elena Mizulina, Irina Yarovaya atau Irina Rodnina tidak mungkin diingat oleh para deputi dan penulis undang-undang yang mendiskriminasi karena jenis kelamin mereka.
Foto: Mikhail Japaridze / TASS